
MASIH ingat panorama Tana Toraja di selembar kartu pos? Ada rumah adat (tongkonan) dan lumbung (alang), yang atapnya menjulang ke langit. Ada pula hamparan padi yang dipagari pohon kelapa dengan kerbau yang gemuk-gemuk. Pesona seperti itu salah satunya dimiliki Kampung Kete Kesu.
KETE Kesu (atau Ke’te Kesu) ibarat satu titik dari sekian banyak situs obyek wisata di Tana Toraja (Tator). Hanya saja, hamparan hijau yang biasanya berupa hamparan padi, di musim kemarau berubah menjadi hamparan rumput.
Kete Kesu berada dalam wilayah Lingkungan Bonoran, Kelurahan Tikunna Malenong, Kecamatan Sanggalangi. Dari pusat kota wisata Rantepao, jaraknya sekitar 4 kilometer. Untuk mencapai daerah itu sangat mudah. Dari jalan poros antara Makale (ibu kota Tana Toraja) dan Rantepao, pengunjung berbelok ke jalan kecil sejauh 3 kilometer yang bisa dilewati dua kendaraan. Hanya di beberapa ruas jalan selain menyempit, terlihat aspal jalan mengelupas dan berlubang-lubang.
Sebagai tempat wisata, Kete Kesu cukup lengkap, terutama bagi yang hendak meneropong potret siklus kehidupan tradisional orang Toraja. Mulai kehidupan dengan segala aktivitas sampai prosesi kematian. Di Kete Kesu, ada tongkonan, lumbung, rante (tempat upacara), liang (lokasi pemakaman), sampai museum. "Tidak semua lokasi lengkap. Kete Kesu termasuk yang cukup lengkap mulai tongkonan dan alang, juga ada lokasi pemakaman di belakang kampung," ujar Idin Sarungallo, penduduk Kete Kesu.
Tana Toraja adalah potret tradisi megalitik dari zaman prasejarah. Di Indonesia, seperti halnya kawasan Asia Tenggara, kebudayaan megalitik (megalitik tua dan megalitik muda) diperkirakan berkembang antara 2500-1500 Sebelum Masehi. Penemuan sejumlah situs dan artefak seperti menhir (simbuang) serta pemujaan arwah leluhur memperlihatkan corak kebudayaan itu.
Contoh sederhana, pembuatan patung (tau-tau) mengingatkan pada perilaku pembuatan arca-arca di masa purba. Melihat pola dan sistem kepercayaan yang ditemui saat ini, tak mengherankan bila para peneliti menilai tradisi megalitik di Tana Toraja masih berlangsung sampai hari ini, seperti di Flores, Nias, dan Sumba.
Potret itu juga terasa di Kete Kesu. Di perkampungan itu ada enam tongkonan, yang berderet dari barat ke timur. Semuanya menghadap ke utara. Tongkonan adalah rumah yang diwarisi turun-temurun. Tongkonan mempunyai harta berupa aluk todolo (agama, norma), lahan persawahan dan kebun, lingkungan sekitar untuk menanam bambu atau buah-buahan, lahan ternak, tempat upacara, benda-benda pusaka, dan areal pemakaman. Tetapi semua itu bukan hanya berfungsi buat keluarga, melainkan juga bernilai sosial untuk masyarakat sekitar. Maka tongkonan menjadi sumber kehidupan masyarakat.
Memandangi rumah-rumah panggung itu tampak begitu anggun. Atap yang khas seperti perahu, menjulang ke langit. Di hampir semua bagian dipenuhi ukiran. Di bagian depan tanduk dan kepala kerbau tersusun rapi, boleh jadi merupakan persembahan pemilik tongkonan.
Sebagai rumah panggung, tongkonan seakan memiliki kaki-kaki, yang ketinggiannya hampir dua meter dari tanah. Jadi untuk masuk ke rumah, harus menggunakan tangga. Tetapi kini hidup naik-turun ke tongkonan menjadi masalah tersendiri. Terutama merepotkan orang-orang tua.
Karena itu, tongkonan tidak ditempati lagi. Mereka justru membangun rumah yang langsung berfondasi di atas tanah, di belakang tongkonan. Tongkonan selain menjadi obyek turis, hanya digunakan untuk bersantai atau pertemuan.
SELAIN tongkonan, Kete Kesu juga punya 12 lumbung. Lumbung yang berhadapan dengan tongkonan itu tempat menyimpan hasil panen.
Sementara benda-benda bersejarah disimpan di museum. Diperkirakan benda-benda itu berusia puluhan bahkan ratusan tahun. Ada senjata tajam seperti parang dan keris, keramik dari China, kain dari India, patung, ukiran, dan benda-benda lain yang diduga bernilai sejarah. Bahkan ada bendera Merah Putih yang sudah lapuk, konon yang pertama dikibarkan di Tana Toraja.
Sayangnya, belum ada informasi detail tentang benda-benda tersebut, mengenai asal-usulnya maupun fungsi historis di zamannya. "Kami tengah melakukan pendataan, menata, dan mengumpulkan informasi itu. Soalnya, barang-barang ini dikumpulkan dari rumah-rumah. Di rumah-rumah kan tercecer. Museum ini merupakan upaya penyelamatan," kata Idin, pemegang kunci museum.
Bergeser ke arah belakang kampung dalam jarak sekitar 100 meter terdapat bukit yang di sekelilingnya ditumbuhi pohon bambu dan kakao. Di dinding-dinding bukit kapur (karst) itulah lokasi pemakaman. Ada bangunan makam yang dibangun dari bahan semen (patene), patung leluhur (tau-tau), dan wadah mayat atau peti mati (erong). Tampak erong yang menyerupai bentuk perahu, kerbau, dan babi digantungkan di dinding bukit. Sebagian besar sudah dimakan usia alias tua, tampak kusam dan lapuk.
Bahkan beberapa di antaranya sudah berlubang sehingga kerangka manusia tercecer di dinding bukit, termasuk bagian tengkorak. "Karena sudah tua, (erong) pernah jatuh. Kemudian kami perbaiki lagi. Kerangka-kerangka itu kami susun kembali," kata Idin. Pemakaman, meski terlihat kusam, tetap masih dipelihara dengan baik. Maklum, orang Toraja sangat menghormati arwah leluhur.
Sebelum berlalu dari Kete Kesu, tentu pandangan tak bisa berpaling dari cenderamata atau suvenir yang dihias ukiran khas Toraja. Memang, selain sebagai situs sejarah sekaligus obyek wisata, Kete Kesu dikenal sebagai pusat ukiran. Meski tak semua memiliki keahlian yang diwarisi turun-temurun itu, rata-rata penduduk membuka kios cenderamata.
Ada nampan, tatakan gelas, gelang, kalung, patung, hiasan dinding, dan lukisan. Semuanya bermotif hiasan hasil lukisan atau ukiran mereka. Tatakan gelas dijual Rp 1.000, nampan Rp 20.000-Rp 25.000, sedangkan lukisan yang diukir bisa jutaan rupiah. "Kami jual suvenir untuk tambahan penghasilan. Penghasilan utama penduduk tetap dari pertanian," ujar Linggayo (65), juru parkir kendaraan para pelancong.
Tetapi, sejak krisis ekonomi dan gonjang-ganjing politik terlebih lagi sejak bom Bali, seperti halnya di seluruh kawasan Tator, Kete Kesu seakan kehilangan pengunjung. "Sejak Pak Harto turun dan terlebih lagi kasus bom Bali, tamu-tamu jauh berkurang. Akibatnya, penghasilan menurun. Kalau dulu bisa mendapat Rp 300.000 per hari, sekarang dapat Rp 150.000 sudah bagus," kata Alius yang tengah mengukir papan berukuran 70 x 18 sentimeter di kiosnya. Alius adalah putra mendiang Mayanna Limbangallo, pengukir yang pernah diundang berpameran di Jakarta pada zaman Soeharto.
Di perkampungan pada ketinggian 846 meter di atas permukaan laut (dpl) itu saat ini ada 20 keluarga atau sekitar 200 jiwa penduduk. Sebagian besar adalah petani. Ada juga penggembala kerbau, pengukir, dan juga pegawai negeri sipil.
Selain Kete Kesu, yang merupakan salah satu kampung megalitik, di Tator masih banyak obyek lainnya. Ada goa tempat menyimpan mayat di Londa, lokasi pemakaman di tebing di Lemo, perkampungan Sangalla, dan sederet lokasi menarik lainnya yang bisa dikunjungi. Semuanya bisa direngkuh karena jaraknya berdekatan. (Subhan SD)
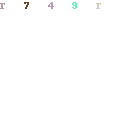


 MASIH ingat panorama Tana Toraja di selembar kartu pos? Ada rumah adat (tongkonan) dan lumbung (alang), yang atapnya menjulang ke langit. Ada pula hamparan padi yang dipagari pohon kelapa dengan kerbau yang gemuk-gemuk. Pesona seperti itu salah satunya dimiliki Kampung Kete Kesu.
MASIH ingat panorama Tana Toraja di selembar kartu pos? Ada rumah adat (tongkonan) dan lumbung (alang), yang atapnya menjulang ke langit. Ada pula hamparan padi yang dipagari pohon kelapa dengan kerbau yang gemuk-gemuk. Pesona seperti itu salah satunya dimiliki Kampung Kete Kesu.